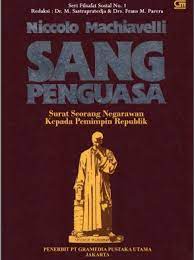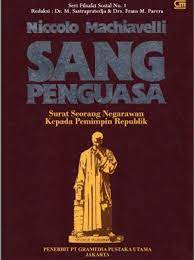1120. Mendadak Setia
07-04-2023
Urusan sepakbola itu tiba-tiba saja banyak yang mendadak setia, setia pada Soekarno, setia pada konstitusi. Seakan segala pengkhianatan terhadap Soekarno, atau keranjingan melupakan amanat konstitusi itu sudah dilupakan. Enak banget jadi orang. AHY, ketua umum Partai Demokrat itu benar juga, salah satu tempat untuk menyuarakan dengan lantang bahwa kita sebagai bangsa berkeyakinan bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan adalah di forum PBB. Suka atau tidak, paling tidak itu masih merupakan tempat terhormat untuk menyuarakan apa yang menjadi pandangan bangsa. Tentu itu hanya salah satu jalan, tetapi sudahkah itu dijalankan? Datang di forum Sidang Umum PBB-pun tidak pernah, kecuali saat pandemi via zoom.
Jalan lain adalah konsekuen dengan apa-apa yang diyakini, termasuk soal ‘penjajahan di atas dunia’: apakah ‘penjajahan’ di atas republik di seberang jembatan emas itu sudah benar-benar dihapus? Apa esensi dari penjajahan? Segala penjajahan selalu akan terkait dengan ketidak-bebasan dan kebrutalan. Kebebasan akan selalu dikekang, dan kebrutalan[1] akan memperoleh pembenarannya. Bahkan di ruang-ruang persidangan pula. Silahkan keluarkan segala kutuk jika itu memang perlu dikutuk, apalagi suasana kebatinan konstitusi sangat peka terhadap situasi seperti itu, tetapi dalam saat bersamaan: ngaca! Jangan sampai cuma pintar cari ‘kambing hitam’[2] saja. *** (07-04-2023)
1121. Zero Defect
08-04-2023
Dalam dunia ‘kendali mutu’, suka atau tidak nama Phillip B. Crosby biasanya akan muncul, langsung atau tidak. Warga AS itu begitu demen-nya soal mutu sepanjang hidupnya. Bagaimana ‘visible hand’ –katakanlah segala sesuatu terkait dengan manajemen, mampu menjaga hasil dengan tetap mempertahankan standar mutu tertentu. Dalam dunia yang semakin kompetitif, quality assurance jelas tidak boleh dilupakan. Bahkan sekitar satu dekade setelah Crosby semakin aktif dalam soal ‘pengendalian mutu’ ini, Koentjaraningrat di awal tahun 1970-an pernah mengingatkan bahwa mentalitas meremehkan mutu[1] itu merupakan salah satu yang sungguh tidak sesuai dengan pembangunan. Bagaimana setelah 50 tahun (!) Koentjaraningrat menulis hal-hal tersebut?
Apakah soal mutu, soal quality assurance ini hanya ada di pasar saja, atau di rantai produksi di sebuah korporasi? Dan meredup di ranah masyarakat sipil dan negara? Tentu tidak. Soal mutu di masyarakat sipil paling tidak adalah soal penghayatan. Katakanlah semacam ‘kode-kode kultural’ soal mutu semestinyalah ada dalam masyarakat sipil. Sehingga ia dengan mudah saja memberikan apresiasi pada hal-hal terkait dengan mutu, baik dalam masukan, proses maupun keluarannya. Dan juga menjadi peka terhadap laku-laku tidak bermutu. Tetapi di ranah negara jelas tidak cukup berhenti soal ‘penghayatan’ saja. Jika tidak mau dimakan oleh kekuatan pasar, negara harus mampu menjaga diri sebagai lembaga yang bermutu juga. Itupun masih saja belum jaminan negara akan mampu ‘mengatasi’ kekuatan pasar, karena seperti banyak dikatakan, politik adalah seni dari kemungkinan.
Yang tidak boleh dilupakan adalah ‘peringatan’ dari YB. Mangunwijaya, yang menandaskan bahwa “sifat, watak, wajah, dan suasana suatu bangsa ditentukan langsung oleh derajat kemampuan, seni, dan efektivitas bangsa itu dalam mengendalikan kekuasaan.”[2] Dan menurut Harold J. Laski, khalayak hanya akan mampu menghayati karakter sebuah negara melalui pemerintahannya. Tidak lain-lainnya. Melalui katakanlah, orang-orang kongkret yang sedang mengelola negara. Perilaku dan kebijakan-kebijakannya. Bukan melalui sila-sila Pancasila yang dipigura dan digantung di dinding, misalnya. Ada bermacam ‘rute’ dalam upaya ‘pengendalian kekuasaan’, dan terutama adalah rute ‘hasrat vs hasrat’. Rute ‘hasrat vs hasrat’ ini sebaiknya dimaknai tidak hanya dalam konteks ‘antar-lembaga’, tetapi juga menunjuk pada ‘kualitas diri’. Jelas tidak dimaksudkan bahwa ‘pengendalian kekuasaan’ itu akan diletakkan di pundak ‘orang baik’ saja misalnya, tetapi bagaimanapun juga ‘kualitas diri’ itu adalah ‘syarat mutlak’-nya. Lihat misalnya, di negara-negara demokratis yang mampu menyejahterakan warganya, kesalahan-kesalahan ‘kecil’ saja bisa mendorong pejabat itu mengundurkan diri, atau didesak untuk mundur. Bukan masalah ‘sok-suci’ atau ‘sok-baik’, tetapi bagaimanapun juga, mengingat kutipan Mangunwijaya di atas, menjadi terlalu besar yang dipertaruhkan jika kemudian ‘tak tahu diri’.
Bagaimana soal ‘kualitas diri’ dari pengelola negara di negara demokratis dan berdasarkan hukum’? Bagaimana menjadi ‘bermutu’ di ‘negara berdasarkan hukum’? Bagi kebanyakan, hukum bisa menjadi salah satu sumber etika. Taat hukum juga bisa dihayati sebagai yang beretika. Tetapi bagi ‘yang terpilih’, entah karena profesinya, atau posisi dalam masyarakat luas, bahkan untuk jabatan-jabatan tertentu dalam sebuah korporasi misalnya, atau terlebih dalam jabatan-jabatan publik, etika akan ‘mendahului’ hukum. Mereka punya semacam ‘code of conduct’ dalam bertindak jauh sebelum hukum akan men-‘supervisi’-nya. Mereka juga punya semacam ‘code of ethics’ yang akan sangat berpengaruh dalam pembuatan keputusan jauh sebelum hukum memberikan batas-batasnya. Maka soal etika ini bisa dikatakan sebagai ‘alat deteksi dini’ akan bermutu atau tidaknya sebuah proses, terlebih jika diletakkan di ranah ‘negara berdasarkan hukum’. Orang-orang yang sudah jelas-jelas melanggar etika sebaiknya minggir dari jabatan-jabatan publik. Dia sudah gagal dalam hal yang sungguh mendasar dalam ranah ‘negara berdasarkan hukum’. Etika bisa dibayangkan pula sebagai pintu masuk utama dalam paradigma ‘zero defect’ di ranah jabatan-jabatan publik. Itu kalau kita memang mau hidup bersama ini semakin ‘berkualitas’. *** (08-04-2023)
[1] Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, hlm. 45
[2] https://www.pergerakankebangsaan.com/321-Wajah-Sang-Perantau/
1122. Koalisi Faustian
08-04-2023
Ternyata tidak hanya ‘faustian bargain’ dikenal, tetapi juga ada ‘koalisi faustian’. Si-pelaku-pelaku ‘faustian bargain’ itu kemudian membangun sebuah kerjasama nan erat, sebuah koalisi besar-nya. Sik-Faust yang mau-mau saja menyingkirkan apa-apa yang berharga, apa-apa yang mulia, demi mendapatkan bantuan kekuatan dari si-iblis Mephistopheles untuk lebih berkekuatan, untuk lebih kaya-raya, untuk lebih mampu menarik hati gadis muda pujaannya. Bagaimana akhir dari drama ‘koalisi faustian’ ini? Kita tunggu saja babak berikutnya …. *** (08-04-2023)
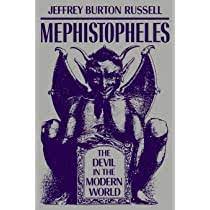
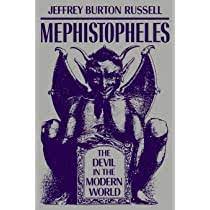
1123. Sandera Kasus Dan Yang Dipertaruhkan
09-04-2023
Sama-sama mbèlgèdès-nya, mana yang lebih mbèlgèdès, si-penyandera atau si-tersandera? Mana yang akan lebih besar dampak merusaknya? Dari si-penyandera atau si-tersandera kasus? Apa yang terjadi terkait dengan gejolak hasrat akan kuasa ketika ia dengan mudah dapat membalikkan nasib orang-orang karena kasus-kasus yang melilitnya? Apakah ini adalah puncak dari apa yang disebut Manuel Castells sebagai ‘politik skandal’ itu? Dimana olah skandal menjadi ‘senjata’ penting dalam olah kuasa melalui jalur politiknya. Skandal yang semakin cepat merebak-menyebar untuk ‘dikonsumsi’ oleh khalayak melalui bermacam kemajuan teknologi komunikasi. Dan dengan cepat pula potensi ‘delegitimasi’ itu membesar. Bad news is a good news, demikian ungkapan lama serasa masih bisa digunakan. Atau dalam pendapat Toynbee mengenai ‘hukum pertukaran kebudayaan’, semakin rendah nilai budaya semakin mudah diserap, tetapi semakin tinggi budaya maka semakin besar pula resistensinya.
Dari asal katanya, skandal bermakna sebagai damage to one's reputation, atau juga, person whose conduct is a disgrace.[1] Jika dilihat lebih jauh, ini adalah soal ‘batas’. Ketika sebuah reputasi mengalami keretakannya karena ada batas-batas yang dilanggarnya, atau soal batas antara kelakuan baik dan buruk. Ketika bermacam batas itu dilanggar maka semestinya ia akan menghadapi ‘pengadilan’ akan skandal-nya. Entah itu yang berujung pada sangsi sosial atau bahkan sampai masuk penjara. Tetapi karena berkembang relasi penyandera-tersandera, maka konsekuensi dari dilanggarnya batas-batas itu kemudian perlahan melenyap, Yang sedang terlilit skandal itu tetap saja masih bisa memegang reputasi-nya –seolah-olah, masih juga bisa pecingas-pecingis di depan publik. Di luar ini akan nampak seakan hanya berhenti dalam soal kendali, bagaimana si-penyandera kasus memegang kendali atas si-tersandera. Tetapi dengan adanya sistem mirror-neuron dalam otak kita, ‘kebahagiaan’ si-tersandera karena batas yang sudah dilanggarnya itu seakan melenyap komplit dengan segala konsekuensinya, ternyata itu juga akan berpengaruh dalam diri si-penyandera. Ia bisa-bisa menjadi juga ingin menikmati ‘kebahagiaan’ dari hilangnya batas. Melalui rute mimesis dalam lorong-lorong sistem mirror-neuron itu. Atau katakanlah, seakan terjadi seperti apa yang digambarkan Hegel sebagai ‘dialektika tuan-budak’ itu. Atau juga berkembang semacam ‘sindrom Stockholm’ di dua arahnya.
Apa akibatnya dalam diri si-penyandera ketika penghayatan terhadap batas itu -sadar atau tidak, perlahan juga menipis? Maka bisa dikatakan bahwa soal sandera kasus ini, daya rusak terbesarnya bagi hidup bersama justru ada di si-penyandera, karena bagaimanapun si-penyandera itu pastilah lebih powerful dibanding si-tersandera. Bahkan dari sisi sik-tersandera, katakanlah, toh itu bagian dari ‘bertahan hidup’-nya juga. Hidup yang sudah seakan tenggelam dalam pasir penghisap sampai sebatas leher. Apa saja tentu akan diraihnya, termasuk juga ketika iblis mengulurkan tangannya. *** (09-04-2023)
1124. Salam Dari 'Sang Penguasa'!
Seri Nasib Cuk Banteng
10-04-2023
Ketika sang pangeran telah menguasai Rogmana dan merasa perlu untuk menenangkan dan membuat Rogmana patuh kepada pemerintahannya, ia menunjuk Remirro de Orco, seorang yang kejam, cakap dan diberinya segala kepercayaan dan wewenang. Dalam waktu yang singkat, Remirro telah berhasil memulihkan tata tertib dan persatuan dan mendapatkan pujian besar.
Kemudian sang pangeran mengambil keputusan bahwa wewenang yang berlebihan ini tidak diperlukan lagi, karena bisa tumbuh dan tak dapat dikendalikan lagi. Karena itu ia mendirikan di tengah propinsi sebuah pengadilan sipil, yang dipimpin oleh seorang ketua yang sangat terkenal. Setiap kota mempunyai perwakilannya di pengadilan tersebut. Dengan menyadari bahwa kekejaman dari masa lalu telah banyak menimbulkan kebencian padanya, sang pangeran bertekad untuk membuktikan bahwa kekejaman yang ditimpakan, bukanlah merupakan tindakannya, tetapi dilakukan oleh sifat kejam para menterinya.
Cesare menunggu kesempatan baik ini. Kemudian, pada suatu pagi, tubuh Remirro ditemukan terpotong dua di lapangan Cesena bersama sepotong kayu dan sebilah pisau berdarah di samping tubuhnya. *** (*)
*) Niccolo Machiavelli, Sang Penguasa, Penerbit Gramedia, 1987, hlm. 29-30