1455. Salam Dari 'Sang Penguasa'! (Seri Cuk Tak-Li-Lak)
05-07-2024
Nasib Cuk Tak-Li-Lak[1]
Ketika sang pangeran telah menguasai Rogmana dan merasa perlu untuk menenangkan dan membuat Rogmana patuh kepada pemerintahannya, ia menunjuk Remirro de Orco, seorang yang kejam, cakap dan diberinya segala kepercayaan dan wewenang. Dalam waktu yang singkat, Remirro telah berhasil memulihkan tata tertib dan persatuan dan mendapatkan pujian besar.
Kemudian sang pangeran mengambil keputusan bahwa wewenang yang berlebihan ini tidak diperlukan lagi, karena bisa tumbuh dan tak dapat dikendalikan lagi. Karena itu ia mendirikan di tengah propinsi sebuah pengadilan sipil, yang dipimpin oleh seorang ketua yang sangat terkenal. Setiap kota mempunyai perwakilannya di pengadilan tersebut. Dengan menyadari bahwa kekejaman dari masa lalu telah banyak menimbulkan kebencian padanya, sang pangeran bertekad untuk membuktikan bahwa kekejaman yang ditimpakan, bukanlah merupakan tindakannya, tetapi dilakukan oleh sifat kejam para menterinya.
Cesare menunggu kesempatan baik ini. Kemudian, pada suatu pagi, tubuh Remirro ditemukan terpotong dua di lapangan Cesena bersama sepotong kayu dan sebilah pisau berdarah di samping tubuhnya.[2] ***
[1] Tak-Li-Lak: Ndas-é Botak, Peli-né Galak
[2] Niccolo Machiavelli, Sang Penguasa, Penerbit Gramedia, 1987, hlm. 29-30
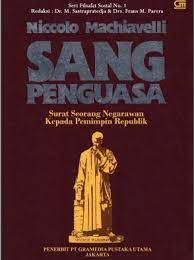
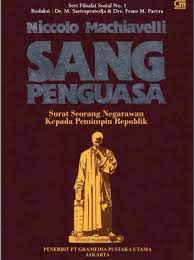
1456. Machiavellian Moment
06-07-2024
The Machiavellian Moment adalah buku karangan J.G.A. Pocock (1924 – 2023), terbit pertama kali tahun 1975, oleh Princeton University Press. Dalam edisi tahun 2017, Penerbit memberikan overview: “Pocock shows that Machiavelli’s prime emphasis was on the moment in which the republic confronts the problem of its own instability in time, which Pocock calls the “Machiavellian moment.” Pada tahun 2017 (edisi bahasa Inggris, 2018) terbit buku karya Patrick Boucheron, Machiavelli, The Art of Teaching People What to Fear. Buku ‘Sang Penguasa’ yang merupakan ‘kumpulan surat-surat’ Machiavelli (1469 – 1527) itu diberikan konteksnya. Dari dua buku itu kita bisa membayangkan pesannya, justru yang ditulis Machiavelli itu adalah hal-hal yang sebaiknya dihindari. Atau kita bisa membayangkan Machiavelli sedang menunjukkan bagaimana sebuah res-publika akan mengalami pembusukannya, akan mengalami instabilitas-nya. Atau kalau melihat dari tulisan Thomas Hobbes (1588 – 1679) dalam Leviathan, jangan hanya berhenti pada bagian pertamanya saja, dimana pada bagian itu dibahas soal ‘manusia apa adanya’.
Jika kita membayangkan perjalanan panjang si-‘manusia apa adanya’ itu, segera nampak di sana-sini terbangun bermacam peradabannya. Dia nampak sudah semakin tidak ‘telanjang’ lagi tetapi bermacam ‘baju’ peradaban telah dipakainya. Apapun jalan yang ditempuh, dan bagaimana percepatannya bisa berbeda-beda juga. Situasi republik di sepuluh tahun terakhir adalah contoh telanjang bagaimana ‘machiavellian moment’ itu sungguh berdampak. Sungguh seakan bermacam ‘kemajuan peradaban’ sedang dipreteli satu demi satu, seakan pula hidup bersama semakin mendekat pada ‘manusia apa adanya’ yang belum tersentuh peradaban. Rusak, sungguh rusak-rusakan. Tetapi mengapa tidak hanya masa lalu yang sering dikhawatirkan bisa-bisa sampai di bibir jurang pelupaan, tetapi adalah juga (rusak-rusakannya) masa yang sedang dijalani ini?
“REAL POWER IS –I don’t even want to use the word – fear.” This sentence could have been written by Niccolo Machiavelli. It was spoken by Donald Trump in March 2016 when Trump was still only a candidate for the U.S. presidency, and these words now appear as the epigraph to Bob Woodward’s book Fear: Trump in White House. Demikian Patrick Boucheron yang orang Perancis itu, membuka bagian Introduction bukunya, Machiavelli: The Art of Teaching People What to Fear. Bagaimana jika bermacam ketakutan itu ditebar dalam diri manusia yang menurut Herman Broch selalu saja menggendong ‘kesadaran temaram’ itu? Apakah seperti dinampakkan oleh sebagian pemilih di AS sono, setuju dengan tawaran program-program Partai Demokrat tetapi akhirnya memilih Republik karena soal (kepemilikan) senjata? Atau mendadak rabun dekat terhadap perilaku pejabat korup, sewenang-wenang, semau-maunya, brutal, penuh kebohongan, hanya karena di jauh sana ada bermacam atraksi tentang radikalisme? Maka paling tidak sepuluh tahun terakhir mestinya memberikan kesadaran tentang apa-apa yang sebenarnya memang perlu ‘ditakuti’ atau katakanlah, diwaspadai. Dan itu sebenarnya tak jauh seperti yang digambarkan oleh Machiavelli sekitar 500 tahun lalu. Digambarkan oleh Machiavelli dari lembah hitamnya manusia, tanpa basa-basi. *** (06-07-2024)
1457. Kegilaan IKN (feat. Bokassa)
1458. Celah Iblis
11-07-2024
Jika Carl Schmitt benar bahwa konsep negara modern adalah sekulerisasi dari konsep teologi maka salah satu ‘kesibukan’ dari negara modern itu adalah bagaimana menjaga bermacam hasrat manusia supaya tidak berubah menjadi ‘kejahatan hasrat’-nya. Tidak menjadi ‘dosa’. Tetapi sebenarnya tidaklah harus dikaitkan dengan konsep teologi, toh sebelum agama dikenal-pun perlahan manusia mulai ‘mengelola’ bermacam hasratnya dalam hidup bersama. Mungkin Carl Schmitt mengatakan itu dalam konteks perjalanan sejarah di Eropa sana, yang mengalami sejarah panjang ‘pergeseran’, dari kosmosentris – teosentris – antroposentris, berpusat pada manusia.
Hari-hari ini paling tidak ada dua pemilihan yang bisa saja menarik perhatian. Pertama, ronde kedua pemilihan parlemen di Perancis, yang seakan golongan ‘kanan jauh’ itu sedang dikeroyok supaya tidak mencapai kemenangan mayoritasnya. Repot kalau Perancis di tangan sayap ‘kanan jauh’ itu, begitu kira-kira salah satu argumennya. Kemarin ronde-putaran kedua telah dilaksanakan, dan ternyata berhasil menjungkir-balikkan dominasi dari sayap kanan-jauh sebelumnya. Partisipasi pemilih dalam putaran kedua mencapai hampir 60%, tertinggi selama empat-puluh tahun terakhir. Sayap kanan-jauh yang di putaran pertama memimpin perolehan suara, di putaran kedua setelah ‘dikeroyok’ menjadi terseok-seok di peringkat ketiga. Apakah Brexit tahun 2016 itu akan terjadi jika dilakukan dua putaran? Nampaknya yang pro-EU saat itu merasa percaya diri dan agak terlena. Tak jauh dari Macron dkk pada putaran pertama, untung ada putaran kedua. Strategi dan taktik dirubah ditambah dengan mobilisasi pemilih, atau katakanlah membangunkan para pendukung yang masih tidur.
Kedua, pemilihan di Inggris dimana Partai Buruh menang telak atas Partai Konservatif yang sudah berkuasa hampir 15 tahun. Yang menarik di Inggris adalah pergantian kekuasaan itu bisa dikatakan hanya dalam hitungan jam, dalam arti bahkan baru berdasarkan exit-poll saja Rishi Sunak yang menjabat PM sekaligus pimpinan Partai Konservatif sudah menyatakan kalah, dan bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Segera saja ia siap-siap keluar dari kantor, dan Keir Starmer, pimpinan Partai Buruh siap-siap masuk kantor sebagai PM baru. Langsung memimpin rapat.
Banyak analisis yang bisa muncul dari dua peristiwa di atas, tetapi yang jadi fokus tulisan ini adalah soal ‘peralihan kekuasaan’ yang terjadi di Inggris kemarin. Begitu cepat, efisien. Tetapi apakah ini hanya soal efisiensi? Soal monarki, oligarki, demokrasi nampaknya bukanlah sekedar soal si-mono, si-olig (sedikit), dan si-demos, tetapi adalah juga soal ‘waktu’. Dan berurusan dengan ‘waktu’ ini kita juga bisa membayangkan yang dimaksud dengan judul tulisan, ‘celah iblis’.
Baik ‘waktu obyektif’ (waktu katakanlah menurut kalender, jam tangan) atau ‘waktu subyektif’ (internal time, sebagai yang dialami) bisa-bisa akan berbeda penghayatan dalam rejim monarki, oligarki, maupun demokrasi. Monarki maupun oligarki akan lebih menghayati waktu obyektif maupun subyektif-nya seakan sebagai yang ‘tak terbatas’. Jelas berbeda dengan rejim demokrasi. Tetapi menurut Husserl (1859 – 1938) ada waktu yang lebih ‘primordial’, consciousness of internal time. Ternyata ‘waktu subyektif’ masih punya ‘pendasarannya’, sebuah aliran atau flow yang melibatkan retention - primal impression – protention. Katakanlah sekarang ini kita mendengar nada 2 –primal impression, maka nada 1 yang baru saja kita dengarkan ini seakan mengalami retensi, dan nada 3 meski belum terdengar seakan sudah kita antisipasi.
Dalam rejim demokrasi, ‘kematian’ rejim yang sedang berkuasa adalah sebuah kemungkinan. Dan bagaimana sebuah rejim menghadapi ‘kematian’ ini sebenarnya juga akan menunjukkan seperti apa ‘kualitas’ yang digendongnya. Bagaimana ‘antisipasi’-nya terhadap ‘kematian’ itu. Sebuah ‘kematian’ yang sebenarnya ‘tidak bisa diwakilkan’ -harus dihadapi sendiri. Itulah dalam konteks di atas, saat Rishi Sunak mengambil tanggung jawab atas kekalahan partai-nya. Dan kemudian mundur dari pimpinan partai. Tidak main ‘impunitas-impunitas’-an atau ngelès-ngelès-an. Atau kaget-kagetan, kesal-kesalan, geram-geraman. Maka siapa saja yang berkuasa dalam rejim demokrasi, ‘kematian rejim’ semestinya menjadi horison-nya. Sebuah kematian tentu akan mendatangkan kecemasan sendiri, bahkan ketakutan. Dalam menghadapi kematian, sebaiknya jangan dihadapi dengan rasa takut, tetapi ‘cemas’, dan dalam kecemasan itulah kita akan didorong untuk mengambil keputusan-keputusan yang bisa dipastikan akan lebih baik jika didorong oleh rasa takut. Rasa takut, sadar atau tidak, akan mempersempit pilihan-pilihan. Bahkan bisa-bisa akan ada dorongan kuat untuk mengingkari kemungkinan akan adanya kematian itu.
Bermacam ‘aliran’ nada-nada seperti contoh di atas mungkin saja kita hayati sebagai sebuah persepsi. Kita akan selalu berhadapan dengan fakta-fakta, tetapi bagaimanapun juga kita tidak akan lepas dari persepsi kita terhadap bermacam fakta-fakta itu. Lalu bagaimana persepsi akan ‘dididik’? Atau jika kita juga ingat pemikiran van Peursen dalam Strategi Kebudayaan, bagaimana persepsi akan terbangun dalam tahap mitis, ontologis, dan fungsionil? Atau bagaimana peran hasrat di sini? Studi akhir-akhir ini terkait dengan mirror neuron system telah memberikan banyak kemungkinan-kemungkinannya. Teori mimetic-nya Girard dalam teori segitiga-hasrat-nya seakan mendapat penjelasan lebihnya. Bahkan juga dialektika tuan-budak-nya Hegel itu. Maka bisa dibayangkan jika ada pemimpin keranjingan untuk ada di tengah-tengah kerumunan yang mengelu-elukan, berulang dan berulang terlebih di luar masa kampanye, bisa-bisa ‘sekolah persepsi’-nya akan menghasilkan tidak jauh-jauh amat dari denyut kerumunan itu. Kerumunan yang perlahan akan menjadi ‘tuan’-nya. ‘Tuan’ yang bermetamorfosis menjadi ‘aliran’ utama consciousness of internal time. ‘Waktu’ yang akan mendasari penghayatan akan ‘waktu subyektif’-nya. Yang akhirnya secara telanjang tiba-tiba saja ‘masa transisi’ itu menjadi ‘celah iblis’ dengan segala konsekuensinya. Semakin lama ‘masa transisi’ maka iblis-iblis itu akan semakin senang dan menjadi-jadi polah tingkahnya. Apa yang terjadi di Inggris dengan masa transisi hanya dalam hitungan jam itu, seperti disebut di atas, pada dasarnya juga mempersempit ‘celah iblis’ ini.
Tetapi ‘hikayat celah iblis’ ini jelas tidak hanya berhenti pada hal-hal di atas karena bagaimanapun juga terkait dengan proses-proses pemilihan. Dan apa atau siapa yang menjadi semacam ‘axis-mundi’-nya proses pemilihan itu? Tidak lain kalau di republik disebut: KPU. Jika KPU-nya rusak-rusakan maka iblis-iblis itu pasti sudah siap-siap dengan tanpa sungkan-sungkan lagi. Apalagi jika ‘waktu kalender’-nya tersedia cukup lama. *** (11-07-2024)
1459. Saat Buddhi Tak Berdaya
13-07-2024
Bagi yang terlibat dalam manajemen pasti akan melihat peran sangat penting dari, katakanlah: corporate culture. Apa yang dibayangkan Christianto Wibisono tentang Indonesia Incorporated (Yayasan Management Informasi, 1985, Vol. I dan II) kira-kira tak jauh dari bayangan republik yang berdaya saing. Kedua buku tersebut merupakan kumpulan tulisan CW yang sebenarnya ingin mengatakan bahwa untuk berdaya saing itu perlu ‘dukungan’, dan itu adalah dukungan ‘politis’, ‘teknis’, dan ‘sosial’.[1] Terdukung secara ‘sosial’ untuk berdaya saing itu salah satunya adalah terbangunnya ‘corporate culture’ yang memang mak-nyus. Berkembangnya kultur atau kebudayaan yang salah satunya akan mendukung berkembangnya daya saing.
Di Barat dikenal istilah meritokrasi, menunjuk pada sebuah hal excellence. Sejak sekitar tahun 1880, dikenal istilah merit system sebagai lawan dari spoils system.[2] Spoils system yang kadang dikenal sebagai sistem patronase itu. Atau kalau jaman old dalam praktek adalah dengan efektifnya jalur A-B-G, yang semakin nampak akan diulang oleh rejim sontoloyo jaman now. Raksasa China yang sedang menggeliat seperti sekarang ini juga punya istilah yang kurang lebih sama untuk hal meritokrasi ini: shangshangce.[3] Sebuah rute hidup yang lama ‘tertidur’ dan dibangunkan lagi oleh Deng Xiaoping dengan ‘umpan’ jitunya: menjadi kaya itu mulia. Tetapi bagaimanapun masih perlu ‘habitat’ yang tepat sehingga shangshangce ini benar-benar dapat bertumbuh-kembang (lagi). Itulah mengapa kita bisa melihat (salah satu, terpenting) bagaimana para koruptor kemudian dihukum mati, misalnya. Artinya dukungan ‘politis’ memang sungguh serius, tidak tipu-tipu saja. Tidak sok-sok-an gegayaan sambil pecingas-pecingis.
Juga bagaimana kemudian dilakukan benchmarking, patok-duga yang akan mendorong berkembangnya sebuah ‘elan vital’ –energi hidup. Kemajuan Barat-lah (dkk.) yang kemudian dijadikan ‘patok-duga’. Bagi Henri Bergson (1859 – 1941), ‘elan vital’ ini akan mendorong berkembangnya kreativitas, hal yang sangat penting dalam bangunan daya saing. Karena ‘elan vital’ akan juga mendorong keberanian untuk ‘menembus’ batas.
Dalam dunia yang semakin kompetitif ini, apa yang disebut sebagai ‘perang kebudayaan’ itu sangat bisa dihayati sebagai ‘penghancuran daya saing’. Atau kalau meminjam istilah Koentjaraningrat sekitar 50 tahun lalu, justru bertahun terakhir ini secara telanjang yang dikembang-biakkan adalah (1) sifat mentalitas yang meremehkan mutu, jaman now paling telanjang nampak pada keranjingan asal-njeplak-mangap itu, (2) sifat suka menerabas, (3) tak percaya pada diri sendiri, (4) tak berdisiplin murni, dan (5) suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh. Ujung kegilaan dari hal-hal di atas adalah: tak tahu batas. Dan apa yang menjadi korban-terpenting dari tak tahu batas ini? Ke-berpikiran! Berpikir dalam dirinya akan mengandaikan adanya horison, ada batas-batas dimana dengan adanya batas itu bermacam kemungkinan akan lebih menampakkan diri. Meski kadang berpikir itu bisa dihayati sebagai rasa-merasa, tetaplah ia ada dalam ‘batas’ sebuah horison. Apakah batas itu akan diupayakan untuk dimajukan, atau bahkan ‘diatasi’ itu adalah bagian dari usaha manusiawi. Tetapi jika tak tahu batas? Bahkan soal rasa-merasa-pun akan menjadi semakin tumpul juga.
Maka yang dimaksud dalam judul adalah memang berangkat dari akar kata budaya. Buddhi, akal, termasuk soal rasa-merasa menjadi tidak ber-daya lagi. Itulah ketika kebudayaan akan mengalami keretakan besarnya. Dan itulah yang sedang diupayakan oleh rejim sontoloyo jaman now ini. Sungguh, sedang diupayakan, sedang berjalan tanpa sungkan-sungkan lagi: merusak republik. *** (13-07-2024)
[1] Lihat juga, https://pergerakankebangsaan.org/tulisan-75, No. 1447, 1448, 1450.
