1775. Empire dan Culture Shock-nya
12-09-2025
Ketika ditanya soal bukunya bersama Antonio Negri, Empire (2000), Michael Hardt menjawab dalam sebuah wawancara (2018) bahwa ada “three hypotheses constitute the foundation of the book: (1) that no single nation-state is able today to determine global order, (2) that, instead, a mixed constitution is emerging, and (3) that global capital and the world market are determining factors in shaping the global order.”[1] Fokus tulisan ini pada yang kedua, terkait mixed constitution.
Mengambil pendapat Polybius (200 SM - 118 SM) sejarawan Yunani Kuno yang menulis sejarah Kekaisaran Roma dengan waktu tinjaunya sekitar 264-146 SM, mengapa Roma bisa menjadi kuat waktu itu? Salah satu pendapat Polybius karena saat itu Roma mengembangkan mixed constitution, rejim campuran antara monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Bagaimana ini bisa dibayangkan? Mungkin struktur ‘Little Empire’ jaman old di republik bisa membantu, siapa yang duduk di puncak ‘monarki’ sudah jelas, Pak H. Kelas aristokrasinya? Apakah yang disebut sekarang ini sebagai kaum oligarki itu? Bukan, tetapi rekrutan melalui jalur ABG itu. Sedang demokrasi? Demokrasi lebih sebagai alat legalitas saja, maka yang berkembang ‘demokrasi seolah-olah’ saja. Selain sebagai alat legalitas, demokrasi saat itu juga sebagai alat penjinak sik-demos. Maka setiap tahun digelarlah pesta itu: ‘pesta demokrasi’.
Seperti dibayangkan oleh Negri dan Hardt terkait dengan ‘kelas monarki’, Pak H saat itu bukanlah sekedar pribadi yang suka senyum saja, tetapi adalah sosok pemegang kendali penuh atas ABRI (saat itu kepolisian termasuk di dalamnya). Pada awalnya, melalui jalur ABG itulah kelas aristokrat lebih dibangun, tetapi perlahan kemudian semakin diisi oleh apa yang dibayangkan oleh Negri dan Hardt, disesaki oleh kekuatan kaum pemegang modal besar, termasuk kaum oligark itu. ‘Aristokrasi’ yang perlahan mengalami pembusukan. Ranah demokrasi selain digelar dalam nuansa seolah-olah, juga mengalami pukulan cukup telak melalui rute depolitisasi. Aktor-aktor non-state, media massa, dan lain-lain juga dalam nuansa represi hebat.
Maka di jaman old, hegemoni ‘little empire’ sebenarnya ‘dirancang’ dengan bekerjanya secara simultan antara repressive state apparatus dan ideological state apparatus. Dalam bagian akhir perjalanannya, kedua ‘apparatus’ itu mengalami keretakannya. Ideological state apparatus mengalami keretakan ketika terutama jalur B dimana kaum teknokrat bisa dikatakan ikut ada di dalamnya, semakin terdesak oleh ‘kekuatan uang’. Yang ternyata juga ikut merambah pada penyangga utama dari repressive state apparatus. Akhirnya ‘little empire’ itupun menjadi kedodoran, dan ketika para aristokrat Empire (global) itu menggedor-gedor pintu gerbang -‘politik pintu terbuka’, minta supaya dibuka lebar-lebar demi masuknya modal mereka, segera saja ‘little empire’ itu runtuh.
Apa yang membedakan Empire dan ‘little empire’? Jika kita bicara ‘rejim campuran’ maka dalam ‘little empire’ itu jarak antara demos dan ‘kaum aristokrat’ plus ‘monarki’ itu lebih dekat dari yang ada di Empire. Di depan hidung. Jika kita memakai teori segitiga hasrat atau teori mimetic-nya Girard, maka dalam ‘little empire’ akan lebih mudah tumbuh ‘rivalitas’ antara demos dan aristokrat/monarki (yang sebelum terjadi ‘rivalitas’ seakan berposisi sebagai ‘model internal’ bagi demos). Menurut Girard, rivalitas itu bisa ‘dikelola’ dengan menghadirkan ‘kambing hitam’. Tetapi sebenarnya ada pilihan lain, menghadirkan ‘pihak ketiga’ yang dimaui baik oleh demos atau juga kaum aristokrat/monarki, sama-sama mengejar ‘kesejahteraan’, misalnya. Di sinilah peran kaum ‘teknokrat’ diperlukan, dari pada ‘tukang jagal’ sik-kambing hitam. Apalagi dalam modus komunikasi mass-to-mass via jaringan digital-internet seperti sekarang ini, khasiat rute per-kambing-hitam-an ini bisa-bisa berumur pendek saja. Selubung fakta per-kambing-hitam-an itu bisa-bisa akan semakin mudah terkuak saja.
Dimana culture shock-nya? Ada yang merasa sebagai bagian dari kaum aristokrat-nya Empire, padahal ia hidup dalam ‘little empire’. Dimana khalayak kebanyakan itu, sik-demos ada di depan mata. Thomas Piketty dalam Capital in the 21st Century (2014) menyampaikan data bagaimana kesenjangan atau ketimpangan global bahkan sudah tak jauh beda pada abad 18-19 ketika kapitalisme liberal merebak. Termasuk dalam banyak masing-masing negara. Dan itu juga yang akan hadir di depan hidung ‘little empire’. Dalam situasi obyektif seperti itulah ketika ada yang merasa sebagai bagian dari ‘aristokrat global’ dan kemudian pecicilan dengan tanpa beban lagi di tengah ketimpangan yang memang sudah ugal-ugalan, tiba-tiba sik-demos yang ada di depan hidungnya itupun akan bereaksi. Dalam bermacam bentuknya. Dalam nada-nada yang semakin mengeras.
Maka baik rejim Empire maupun ‘little empire’ ini mesti dilawan. Karena pasti pertama-tama yang menjadi korban adalah sik-demos komplit dengan demokrasinya. Yang kedua, jangan sampai yang pegang senjata itu kemudian menjadi alat represi bagi khalayak kebanyakan. Kembali menjadi ‘yang profesional’. Dan tidak ada lagi ‘logika jalur ABG’ atau apapun itu, tetapi bangun sistem yang mendasarkan diri pada meritokrasi. Aktor-aktor non-state seperti disinggung di atas perlu diperkuat secara terus menerus, tetapi jangan dilupakan: ‘revolusi’ partai politik (baca juga: jalur G). Faktanya, terlalu banyak partai politik sekarang ini telah menjadi partai sontoloyo. Dan jangan pernah bermimpi ‘rejim campuran’ ini akan membawa pada kesejahteraan bersama. *** (12-09-2025)
[1] https://greattransition.org/publication/empire-and-multitude
1776. Doppelganger?
13-09-2025
Doppelganger?[1] Tidaklah. Janganlah, dalam hal berikut. Enam tahun lalu para tokoh menemui presiden J di istana negara, terutama terkait masalah ‘pelemahan KPK’. Penuh harapan supaya presiden mau ‘mengurus’ pelemahan KPK ini melalui langkah-langkah yang dimungkinkan. Melalui penerbitan perppu, misalnya. Juga soal demokrasi. Dan lain-lainnya. Pokoknya hal-hal baik terkait penyelenggaraan negara.[2] Hari-hari ini terberitakan para tokoh bertemu dengan presiden P, terutama terkait reformasi kepolisian. Dan juga soal penegakan hukum. Intinya, hal-hal baik terkait penyelenggaraan negara. Sebagai pengingat, kami link tulisan enam tahun lalu, klik: https://www.pergerakankebangsaan.com/405-Ayo-Komit-nang-Kebon/
Terimakasih. Semoga berguna. *** (13-09-2025)
[1] Juga buku terbaru Naomi Klein
[2] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190926150821-20-434330/jokowi-bersuara-jangan-ragukan-komitmen-saya-jaga-demokrasi, misalnya. Dan banyak berita lagi.
1777. Bangsaaat ...
13-09-2025
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 731 Tahun 2025
tentang
Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum
Tanggal Penetapan:
21 Agustus 2025
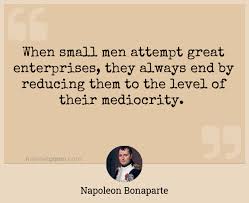
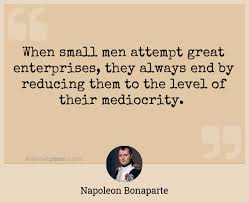
1778. Reformasi KPU!
14-09-2025
Keputusan PKU No. 731 Th. 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik Yang Dikecualikan KPU, ditetapkan 21 Agustus 2025 mempertegas mengapa ‘prahara’ Agustus-September baru-baru ini terjadi. Siapa yang menjadi ‘sasaran kemarahan’ khalayak kebanyakan kemarin-kemarin itu? Atau yang terjadi di Nepal sana? Semakin nampak yang jadi sasaran kemarahan adalah ‘kaum semau-maunya’ itu. Itulah ‘deep frame’ yang semakin lama semakin kuat. Maka jika tiba-tiba ada ‘surface frame’ seperti jogat-joget pethakilan sok-sok-an itu menyeruak di depan hidung, tiba-tiba saja itu dapat cantholannya, mendapat tempat bergantungnya dalam ‘kemarahan terhadap kaum semau-maunya’ itu. Mengapa ‘bangunan atas’ menampakkan diri dalam kemarahan terhadap ‘kaum semau-maunya’? Karena ‘basis’ lebih bernuansa chrematistics dari pada oikos-nomos.[1]
Maka apakah itu ada penunggang gelap, penunggang terang, itu tidaklah menghapus kemarahan terhadap kaum semau-maunya sebagai deep frame. Bahkan jika ada yang ‘merancang’ jauh sebelumnya, mereka (yang merancang itu) salah perhitungan soal deep frame ini, yang sebenarnya sudah sangat berakar dan sulit ‘dibelokkan’, yaitu ‘kemarahan terhadap kaum semau-maunya’. Kemarahan yang mempunyai ‘basis’ terusiknya akibat polah-tingkah kaum chrematisticos itu sudah menjadi begitu ugal-ugalan, dan menghempaskan dengan tanpa beban lagi sik-oikos nomos. Keputusan KPU di atas sungguh dengan telanjang menampakkan diri bahwa yang ada di KPU itu adalah bagian dari ‘kaum semau-maunya’. Mau dibantah sambil kayang atau koprol-pun, dari keputusan KPU di atas saja telah menunjukkan bahwa mereka-mereka yang di KPU itu telah bersekutu dengan ‘kaum semau-maunya’. Bahkan telah menjadi salah satu tendo achilles dari sepak terjang ‘kaum semau-maunya’ itu.[2]
Maka bahkan tidak hanya ‘reformasi KPU’, tetapi ‘revolusi KPU’ diperlukan. KPU (dan Bawaslu) yang telah dibiayai warga negara (triliunan rupiah) melalui pajak-pajaknya, sungguh perlu dilakukan ‘patahan sejarah’. Jika dilakukan audit total termasuk Sirekap-nya itu maka sungguh ada alasan kuat mengapa perlu ‘patahan sejarah’ KPU itu. Terutama aktor-aktor di dalamnya, karena ini bukan saja soal per-KPUan, tetapi juga soal ‘reformasi birokrasi’, paling tidak jika secretariat KPU masuk dalam imajinasi kita. Momentum prakondisi sosial, dan bagaimana prakondisi politik sudah sedikit menampakkan gejala positif -semoga saja terus berlanjut, maka tinggal bagaimana prakondisi teknis ini dibangun (baru) sehingga mampu melawan ‘kaum semau-maunya’ itu. Revolusi KPU (dan Bawaslu) harus menjadi refleksi dari keinginan menegakkan ‘oikos-nomos’. *** (14-09-2025)
[1] https://pergerakankebangsaan.org/tulsn-138, no. 1761, 1762
1779. "Bermain Jarak"
15-09-2025
Bermain sendiri adalah juga soal jarak. Anak kucing yang bermain kelahi-kelahi-an, tentu ia berjarak dengan perkelahian yang sesungguhnya. Perkelahian (sungguhan) antar kucing jantan saat musim kawin, misalnya. Atau ketika ada kucing jantan lain nyelonong ke teritorinya. Yang terjadi bisa-bisa berkelahi sungguhan, bukan bermain-main lagi. Maka bagi homo ludens, ketrampilan dalam soal ‘jarak’ ini bisa-bisa menjadi salah satu hal mendasar. Bahkan pula sebagai animal rationale-pun soal jarak juga ikut ‘bermain’. Atau dalam pemikiran Van Peursen dalam Strategi Kebudayaan, yang membedakan tahap mitis dengan tahap ontologis misalnya, adalah juga soal ‘jarak’.
Mengapa tiba-tiba saja mempermasalahkan soal ‘bermain jarak’? Karena bahkan ketika anak baru belajar berjalanpun perlu ‘jarak’ pula. Ketika jatuh, kadang perlu dibiarkan lebih dahulu meski ia menangis, misalnya. Atau pada titik tertentu kita lepas pegangan tangannya. Atau beberapa tahun lalu kita mendengar slogan kampanye, “sik-J adalah kita”. Seakan antara (calon) pemimpin itu tidak pernah ada jarak dari yang dipimpinnya. Yang kemudian diteruskan setelah kampanye, tidak hanya slogan saja tetapi menjadi terlalu sering ia dinampakkan selalu dalam kerumunan. Sekali lagi, seakan ia telah melebur bersama yang dipimpinnya. Sudah tidak ada jarak lagi. Benarkan pemimpin ‘yang baik’ itu kemudian sama sekali ‘tidak berjarak’ dengan yang dipimpinnya?
Mungkinkah jika pemimpin merasa diri sebagai ‘yang bagus atiné’, seperti Yang Ilahi misalnya, ia merasa harus membangun ‘manunggaling kawula gusti’? Dan jika begitu, bukankah ini serasa ‘terbalik’? Mungkin ‘yang bagus atiné’ itu dengan segala kuasanya sudah mendekatkan diri pada ciptaannya, dan membuka tangan lebar-lebar, maka sekarang tergantung dari kawula, mau nggak untuk berusaha ‘manunggal dengan gusti’? Pernak-pernik terkait ini dan juga pelajaran di masa lalu -juga dari bermacam komunitas, konsep manunggaling kawula gusti ini perlu hati-hati dalam menghayatinya, terlebih di ranah olah kuasa negara yang jelas tidaklah ‘suci’ itu. Orang atau pemimpin yang mabuk kuasa bisa-bisa terjerumus dalam kemabukan parah jika salah dalam penghayatannya. Terlebih jika ia merasa sebagai satu-satunya ‘yang bagus atiné’ itu, seakan merasa sebagai ‘gusti’, sebagai Yang Maha Kuasa saja.
Bahkan dalam konsep ‘manunggaling kawula gusti’ itupun tetaplah ada jarak, tidak serta merta ‘mendadak manunggal’. Jika tidak ada jarak, mengapa itu harus diupayakan lebih dahulu? Tetapi apapun itu, dalam olah kuasa ranah negara, kadang menjadi ‘tidak berjarak’ dengan yang dipimpinnya sering menjadi obsesi sendiri. Kadang pula menjadi hal ‘taktis’ saja. Lebih sebagai hal manipulative. Tentu ini sah-sah saja, terutama ketika dalam masa kampanye. Ketika meniti jalan merebut kuasa. Tetapi setelah kampanye? Saat dalam rentang ‘penggunaan kuasa’?
Dalam ranah demokrasi dimana dikenal pula ada masa pemilihan, setelah pemilihan itu jelas ada jarak antara pemimpin (terpilih) dan yang dipimpinnya. Yang dipimpin -khalayak kebanyakan, akan sibuk kembali pada kesehariannya, dalam dunia ‘privat’nya masing-masing. Sedangkan pemimpinnya? Ia semestinya akan sibuk memenuhi janji-janji kampanyenya, di ruang-ruang publik Dan tentu juga: memimpin. Memimpin sesuai dengan bermacam kesepakatan-kesepakatan, atau katakanlah undang-undang dan peraturan yang ada. Dan sebenarnya, dengan itu pula jarak antara yang dipimpin dan ia terjembatani. Jembatan kedua adalah dialog. Apalagi jika kita bicara politik. Tidak ada politik sebenarnya, jika tidak ada dialog. Bagi pemimpin, hal utama adalah mendengar, sedang dari khalayak kebanyakan: berani bicara. Hanya dengan kedua hal itu maka dialog antara pemimpin dan yang dipimpin akan terjadi.
Maka dalam ‘bermain jarak’, mestinya bermainlah secara berbeda dalam rentang waktu kampanye dan setelah berkuasa. Jika ‘tidak berjarak’ menjadi obsesi penguasa (sik-terpilih) setelah pemilihan, banyak catataan masa lalu ini bahkan bisa menjadi long and gloomy history of man.[1] Dalam ranah olah kuasa negara, ‘tidak berjarak’ itu sering berarti juga: loyalitas, obedience. Maka ada banyak alasan kuat apa yang disebut sebagai ‘relawan’ dalam rentang kampanye itu, setelah pemilihan dibubarkan saja. Setelah pemilihan, suka atau tidak, partai politiklah yang (terutama) akan mengawal. Mengapa? Sebab bagaimanapun juga dengan segala pernak-pernik yang ada dalam partai politik, ia bisa lebih mampu berjarak dengan penguasa. Apalagi partai oposisi. Dan tentu juga aktor-aktor non-state lainnya. Tetapi ‘relawan’? Satu-satunya modalnya adalah obedience itu. SS jaman Hitler itu pada awalnya adalah relawan yang menjaga kemanan dan ketertiban saat ada rapat umum.
Tulisan ini didorong munculnya dua berita, pertama soal tayang video presiden P (beserta program-progamnya) di bioskop dan rencana Apel Kebangsaan yang akan diselenggarakan oleh ‘relawan Prabowo’.[2] Yang pertama itu bagi khalayak kebanyakan, seakan ‘ruang privatnya’ sedang ditelikung saja. Mengapa? Karena di bioskop tayangan seperti itu tidak bisa di-skip, dilewati, karena masing-masing penonton tidak bawa ‘remote control’. Yang kedua, soal ‘relawan Prabowo’ itu, di atas sudah jelas mengapa itu sebaiknya dihindari. Ada peristiwa lain juga, yaitu ketika presiden P datang ke Bali terkait terjadinya banjir bandang itu, ada pemberitaan yang sudut pemberitaan dengan tidak melupakan bagaimana presiden dielu-elukan, seakan sebagai ‘yang bagus atiné’. Tidak ada yang salah dengan itu -boleh-boleh saja, masalahnya adalah bagaimana respon presiden terhadap hal tersebut? Akankah kemudian menjadi ‘besar kepala’ jika itu terberitakan berulang dan berulang dalam bermacam peristiwa?
Beberapa hal di atas jelas bukanlah kebetulan saja. Maka sah-sah saja jika ada yang bertanya, apakah sekitar presiden itu banyak yang bodoh? Atau banyak yang ingin menjerumuskan? Atau jangan-jangan presiden sendiri ….. *** (15-09-2025)
[1] CP Snow: "When you think of the long and gloomy history of man, you will find that far more hideous crimes have been committed in the name of obedience than have been committed in the name of rebellion"
[2] https://www.poskota.co.id/2025/09/14/relawan-prabowo-rapat-persiapan-apel-kebangsaan-desak-presiden-copot-menteri-tidak-loyal?halaman=2
